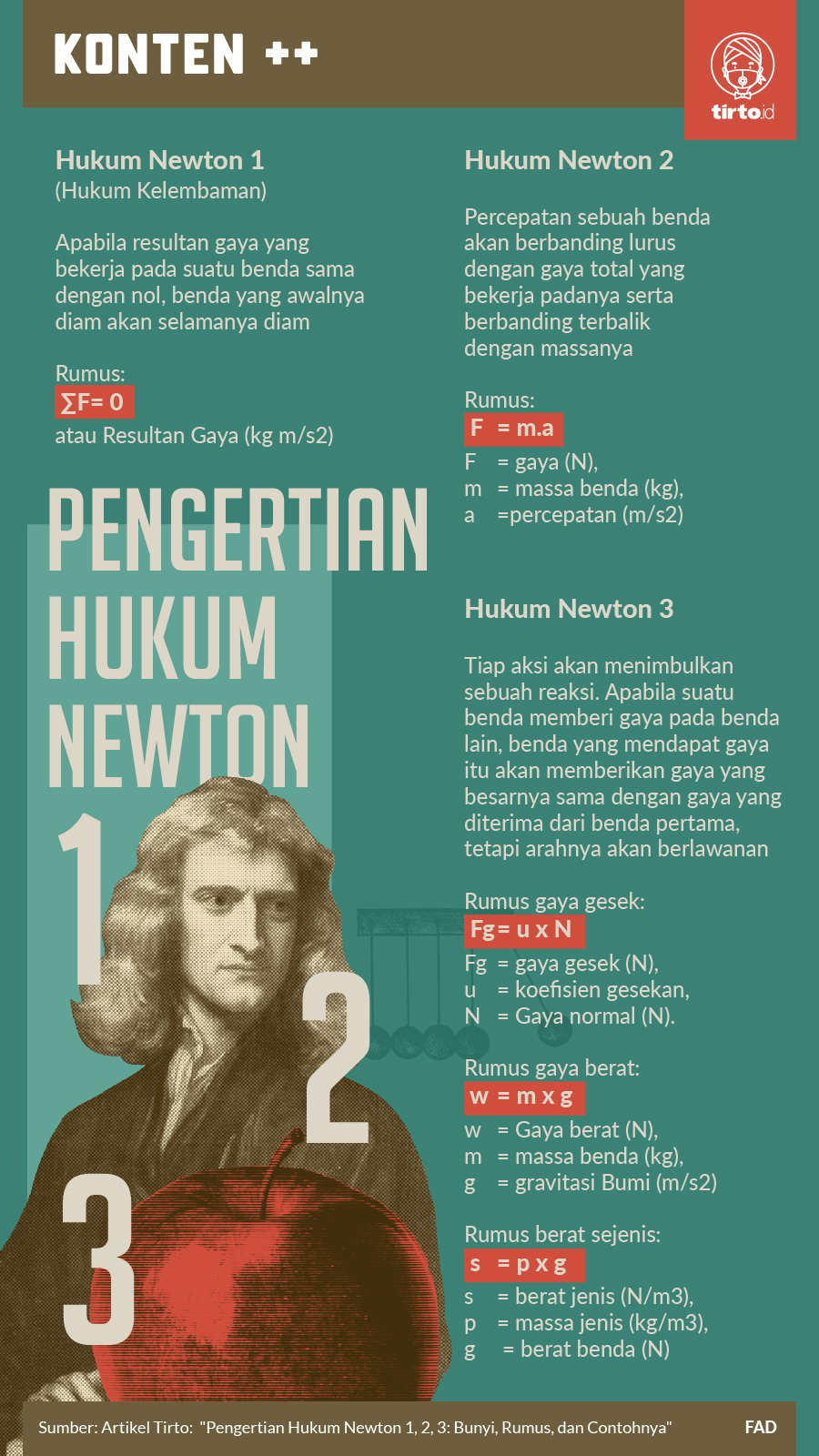Aku mulai terengah menjajari langkahnya. Lalu lalang kendaraan mengisi jeda panjang dalam percakapan kami.
“Lalu kau akan ke mana?” Akhirnya kata itu melompat juga dari mulutku. Hening. Sesaat kemudian, hanya deru kendaraan lagi yang terdengar. Sedang langkahnya semakin panjang saja.
“Akan ke mana kau?!” Suaraku lebih lantang dari yang kuharapkan. Melesat begitu saja dengan buncah yang tidak terjelaskan.
Akhirnya ia menoleh juga. ”Ke mana saja,” hanya itu yang ia katakan. Ia kembali melangkah.
“Apa maksudmu ke mana saja. Kalau kau tidak punya tujuan, tak bisakah kau tetap tinggal?” Ini pertama kalinya aku mendengar ketidakyakinan darinya.
”Tidak. Kau tau aku tak bisa begitu,” ucapnya lemah. Ia berhenti melangkah. Mengambil tempat di bangku jalan. Aku turut duduk di sisinya. Merasa bersyukur ia memilih berhenti sebab napasku mulai tersengal.
”Omong kosong. Aku tidak terima alasan-alasanmu itu. Jika salah, perbaiki. Jika bodoh, belajar. Jika kurang, tambah. Bukan pergi. Bukan menyerah.” Aku mencecarnya dengan prinsip-prisipnya. Berani-beraninya ia mengkhianati prinsip yang selama ini teguh mengakar dalam dirinya. Alih-alih, ia memberikan alasan bodoh sebagai pembenaran.
”Kau benar.” Ia takzim mengaminiku. Kupikir ia akan meyakinkanku dengan argumen-argumennya – seperti yang biasanya ia lakukan. Entah mengapa aku merasa kedinginan. Seolah awan yang baru saja menutupi bulan sabit di langit malam ini turut menyelimutiku. Aku memangku tangan bersilang, menghangatkan diri seraya memanasi percakapan kami.
”Ya, aku benar. Lalu apa ini? Mengambil keputusan tak masuk akal? Senam otak? Kau sedang olahraga jantung? Sky diving saja sana!” Dengan ketus, aku berusaha menggoyahkan pilihannya.
Ia tertawa kecil. “Kau benar,” ia membenarkanku, tampak makin yakin dengan keputusannya. Ini membuatku jengkel. Kuputuskan untuk menyulutnya dengan berkata,”Jika kau tahu mana yang benar, kenapa memilih yang tidak benar?”
”Bagiku, dalam keadaanku, aku tidak bisa memilihnya.” Nada bicaranya sama saja. Ia tidak tersulut. Tidak terdengar api di sana. Ini tidak seperti percakapan kami yang selalu saja hangat atau membara.
”Kenapa?” Tanyaku melemah.
”Kau tidak mengerti.” Ia berkata tegas.
”Memang. Maka jelaskanlah,” aku memintanya dengan frustrasi. Ia mengalihkan wajah. Memandang kemuning cahaya lampu jalan. Di atas sana, ngengat mengelilingi cahaya itu, berdengung-dengung kecil. Ngengat saja berdengung, sedangkan ia? Tak ada yang terucap darinya.
“Kau lari? Kau melarikan diri?” Kutuduh saja ia. Betapa menyebalkan sikapnya ini.
“Terserah kau saja.” Suaranya nyaris tak terdengar. Dia menunduk, menatap ubin trotoar.
”Sekarang kau bersuara, heh? Pengecut.” Ia membuatku putus asa. Aku berharap ia akan membantahku bahkan membentakku atas hinaan itu. Tapi tidak ada yang terjadi. Ia seperti menyetujui kata-kataku. Kepalanya semakin terbenam dalam tunduk. Pandangannya semakin melekat pada bahu jalan.
Hening. Tidak sepatah kata pun ia lontarkan. Sepanjang ingatanku, percakapan malam ini adalah percakapan paling sunyi. Perdebatan yang paling mudah dimenangkan. Tak tampak wajahnya yang membantah. Aku tidak melihat penolakan, aku tidak melihat pertimbangan atau sudut pandang berbeda yang selalu ia obral seperti hari-hari lalu. Aku tidak mendengar sanggahannya. Bahkan tidak dengkusan atau raut jengkel darinya. Perdebatan yang paling mudah kumenangkan, tapi tetap saja rasanya aku yang kalah.
”Apa – apakah menurutmu, di sini sangat buruk? Apakah kau pergi karena di sini sangat buruk bagimu?” takut-takut kulepas juga kalimat itu.
”Tidak. Kau tahu itu tidak benar,” buru-buru ia menyanggahku.
”Lalu, sebegitu bencinya kau pada kami?” Meski tidak siap mendengar jawabannya, kusampaikan juga gundahku padanya.
”Berhakkah aku membenci? Bahkan jika berhak, aku tidak bisa demikian.” Bagiku, ia terdengar putus asa.
”Jadi, kau benar benci, tapi berusaha tidak?” Aku nyaris tidak dapat mendengar suaraku. Pertanyaan itu sebenarnya berputar-putar hanya untuk diriku.
”Tidak. Bukan begitu.” Ia menjawab dengan tenang. Terdengar yakin. Apakah ia sungguh yakin dengan pernyataannya atau aku yang berharap demikian?
”Lalu?” Kuputuskan menuntutnya dengan alasan yang berterima bagiku. Tatapan kami bertemu. Aku tidak mengerti arti tatapannya itu. Sekilas terlihat sendu, sekelebat terlihat ragu, tapi selalu terlihat mampu. Ia tersenyum tipis. Aku tidak dapat membalasnya. Ia kembali membuang pandang.
Sunyi malam mendekap semakin erat. Membuatku sulit bernapas. Aku merasa seperti dipaksa minum soda dan kafein saat diserang gerd. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku seperti dapat mendengar detak jantungku, tapi tidak bisa merasakannya. Yang kutahu, ia akan pergi.
”Kalau begitu, apa kau akan kembali?” Kulepaskan kata, berusaha melarikan diri dari sunyi malam yang mencekam. Entah mengapa rasanya bukan hanya malam yang semakin sunyi, jauh dalam diriku rasa sepi semakin menjadi-jadi.
”Aku tidak tahu,” hanya kata itu yang ia lontarkan. Tidak sedikit pun ia menoleh padaku. Ia memilih untuk memandangi ngengat-ngengat yang mengitari lampu jalan. Selama beberapa saat, kami kembali tak bersuara. Agaknya, percakapan ini telah usai baginya. Namun, tidak bagiku. Meskipun begitu, aku tidak dapat berkata lagi. Kami semakin membenam di bangku kayu, berselimut cahaya jalan, dan tenggelam dalam malam. Hingga akhirnya, Ia bangun dari bangku kayu kemudian melangkahkan kaki. Tidak mengatakan apa-apa. Tidak mengundangku menuju ke tempat yang sama. Aku bergeming. Tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak merasa ingin menyusulnya. Aku tidak yakin bisa menjajari langkahnya lagi. Ia terus saja berjalan. Semakin lama, tubuhnya semakin mengecil dan jarak antara kami semakin membesar.
”Seberapa jauh pun kau pergi nanti, kembalilah. Suatu saat, kembalilah.” Akhirnya, aku dapat membebaskan diri dari cekatan yang menyumpal pita suara dan sulur-sulur tak berwujud yang mengunciku, bersusah-payah meneriakinya, berusaha agar suaraku tidak bergetar. Ia tidak menjawabku. Ia tidak berhenti berjalan. Bahkan ia tidak memberikan isyarat persetujuan atau pun penolakan. Tidak sedikit pun.
Maka, aku menyeru lantang. Kali ini dengan penuh keyakinan. Berharap keyakinan itu akan sampai padanya dan menjadi bekalnya dalam perjalanan panjang. “Jangan lupa pulang! Kau tahu ... pulang!”
Seperti sebelumnya, ia tetap berlalu tanpa menoleh ke belakang. Tanpa menoleh padaku. Tidak sekali pun. Tidak sedetik pun. Perlahan-lahan, ia hilang ditelan malam.